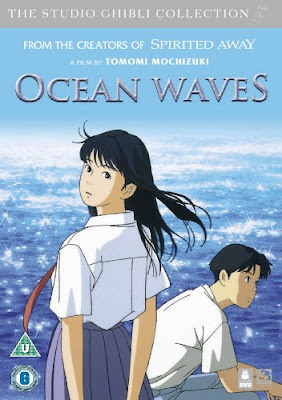Genre : Drama, Thriller | Pemain : Elizabeth Olsen, John Hawkes, Sarah Paulson, Hugh Dancy, Brady Corbet, Louisa Krause | Sutradara : Sean Durkin | Penulis : Sean Durkin | Distributor : Fox Searchlight Pictures | Durasi : 102 menit | MPAA : Rated R for disturbing violent and sexual content, nudity and language
Dari menit-menit awalnya, Martha Marcy May Marlene (MMMM) sudah mulai memancing rasa penasaran saya dengan kesunyiannya. Sekelompok orang terlihat sedang melakukan aktivitas harian mereka di sebuah lahan pertanian yang tampak sepi dan lengang. Ketika malam tiba, para pria menyantap hidangan yang disajikan di meja makan, sedangkan para wanitanya menunggu di ruangan lain dan baru mulai makan setelah semua pria meninggalkan ruangan. Rangkaian adegan pembuka yang singkat ini entah mengapa menguarkan aroma misterius yang membuat saya bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang ini. Apakah mereka ini gambaran dari sebuah keluarga yang masih memegang erat tradisi? Atau hanya semacam komune yang mengasingkan diri dan menetap di daerah pinggiran? Rasa penasaran saya semakin menjadi, ketika di pagi harinya seorang wanita muda dalam kelompok tersebut tiba-tiba melarikan diri, diikuti dengan teriakan seorang pria yang memanggilnya dengan sebutan Marcy May. Sebuah set up yang cukup menjanjikan bagi thriller psikologis seperti ini.
"I know who I am. I am a teacher and a leader, you just never let me be that!"
-Martha-
Dari menit-menit awalnya, Martha Marcy May Marlene (MMMM) sudah mulai memancing rasa penasaran saya dengan kesunyiannya. Sekelompok orang terlihat sedang melakukan aktivitas harian mereka di sebuah lahan pertanian yang tampak sepi dan lengang. Ketika malam tiba, para pria menyantap hidangan yang disajikan di meja makan, sedangkan para wanitanya menunggu di ruangan lain dan baru mulai makan setelah semua pria meninggalkan ruangan. Rangkaian adegan pembuka yang singkat ini entah mengapa menguarkan aroma misterius yang membuat saya bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang-orang ini. Apakah mereka ini gambaran dari sebuah keluarga yang masih memegang erat tradisi? Atau hanya semacam komune yang mengasingkan diri dan menetap di daerah pinggiran? Rasa penasaran saya semakin menjadi, ketika di pagi harinya seorang wanita muda dalam kelompok tersebut tiba-tiba melarikan diri, diikuti dengan teriakan seorang pria yang memanggilnya dengan sebutan Marcy May. Sebuah set up yang cukup menjanjikan bagi thriller psikologis seperti ini.
Selanjutnya, cerita beralih pada kehidupan Marcy May (Elizabeth Olsen)—yang ternyata bernama asli Martha—pasca meninggalkan kelompok tersebut. Kini Martha menetap di sebuah rumah pinggir danau, kediaman sang kakak, Lucy (Sarah Paulson), dan suaminya, Ted (Hugh Dancy). Setelah dua tahun menghilang tanpa kabar, kembalinya Martha yang tiba-tiba itu tentu saja membuat Lucy dan Ted terkejut. Rasa senang dan kesal bercampur jadi satu. Apa yang sebenarnya ada di pikiran Martha dua tahun lalu, ketika ia tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak? Dan apa yang membuat ia akhirnya memutuskan untuk kembali? Martha berdalih bahwa ini berkaitan dengan urusan patah hati. Bahwa kekasihnya berkhianat, sehingga Martha memutuskan untuk meninggalkannya. Sungguh klasik. Namun tentunya penonton tahu, bukan itu alasan sebenarnya. Sedikit demi sedikit, misteri pun terkuak. Seiring dengan rasa penasaran saya yang mulai terbayar.
Sean Durkin, sang sutradara sekaligus penulis naskahnya, mengajak penonton untuk ikut memasuki pikiran Martha, yang bagaikan lorong waktu yang membingungkan, mengaburkan batasan antara masa kini dengan masa lalu. Di sinilah letak kehebatan bagian editingnya. Transisi dari masa kini ke masa lalu Martha saat ia hidup bersama dengan kelompok (yang mungkin bisa dibilang sebagai semacam sekte) itu, ditampilkan dengan mulus. Di beberapa bagian tersebut, saya sempat kebingungan dan berujar, "lho kok?" Sampai akhirnya saya menyadari perpindahan tersebut. Damn, I've been tricked! Seolah-olah saya diposisikan dalam pikiran Martha yang kacau, sulit membedakan mana yang nyata, mana yang sebatas kenangan.
Lalu apa sebenarnya yang membuat Martha nyaris hilang akal? Semua terjawab sedikit demi sedikit dan semakin memuncak saat menjelang akhir. Film ini memang sepi, bukan jenis thriller yang penuh adegan kejar-kejaran antara pembunuh bertopeng dengan mangsanya. Namun jangan salah, anda akan merasakan sensasi ketegangan yang berbeda. Tingkah laku Martha yang semakin aneh dan paranoid, hingga pengungkapan masa lalunya yang gelap, membuat jantung ini berdebar-debar. Coba simak dan hayati adegan saat sang pemimpin sekte, Patrick (John Hawkes), menyanyikan Marcy's Song di depan Martha dan para pengikutnya. Adegan ini sukses membuat saya merinding dan terpaku, seperti Martha yang seolah terhipnotis dengan pesona Patrick yang kharismatik, membawanya semakin jauh ke dalam kegelapan yang membuai. John Hawkes tampil memukau di sini. Lembut, namun auranya mengerikan.
Dari beberapa dialog antara Martha dan Lucy, tersirat bahwa hubungan mereka berdua di masa lalu kurang begitu akrab. Ada masalah dalam keluarga mereka, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit. Ini juga sepertinya yang menjadi alasan mengapa Martha bisa terseret masuk ke dalam sekte pimpinan Patrick. Martha adalah pribadi yang rapuh, merasa terasing di lingkungan keluarganya sendiri. Kondisi inilah yang dimanfaatkan Patrick. Ia merangkul jiwa Martha dengan penuh kelembutan, membuatnya merasa diterima. Hingga akhirnya Martha tersadar, lalu melarikan diri, dengan masih membawa torehan luka hasil perbuatan Patrick. Apa yang dialami Martha selama dua tahun belakangan masih begitu membekas, mempengaruhi kondisi mentalnya. Tingkah lakunya yang tidak wajar semenjak ia kembali tinggal bersama kakaknya, memperlihatkan kegagapannya dalam bersosialisasi di lingkungan "orang normal". Melalui tokoh Martha, MMMM menawarkan sebuah studi karakter yang menarik.
Membicarakan MMMM, tentunya tidak akan lengkap tanpa menyinggung penampilan seorang aktris pendatang baru bernama Elizabeth Olsen. Merasa familiar dengan nama keluarganya? Ya, dia adalah adik kandung dari si kembar tenar, Mary-Kate dan Ashley. Tanpa disangka-sangka, Elizabeth memiliki kualitas seorang bintang yang sebelum ini sepertinya tidak begitu nampak. MMMM bisa dibilang merupakan kendaraannya untuk melesat lebih jauh lagi dalam menggapai status sebagai bintang papan atas Hollywood. Ini bukan pujian asal, karena penampilannya di MMMM memang patut mendapat apresiasi tinggi. Perpindahan timeline yang acak memungkinkan kita untuk melihat karakter Martha dalam emosi yang berganti-ganti pula. Dan Elizabeth Olsen memainkan tugasnya dengan gemilang. Ia sukses menghidupkan karakter Martha / Marcy May / Marlene sehingga tampak believable dan menimbulkan simpati. Mimik wajahnya, gesture-nya, oh my! I gotta say, a star is born.
Jadi, apakah MMMM tidak akan sama tanpa kehadiran Elizabeth Olsen sebagai pemeran utamanya? Bisa jadi. Namun di samping itu, debut layar lebar dari Sean Durkin ini sangat patut diapresiasi dan menjadi awal yang cukup menjanjikan bagi karya-karya selanjutnya di masa mendatang.
Rating : 7.5/10